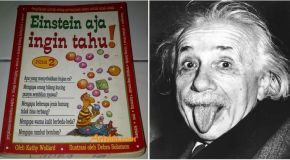Selama Kita Tersesat di Luar Angkasa oleh Maggie Tiojakin
07 May 2014 View : 4162 By : Niratisaya
| Ditulis oleh | Maggie Tiojakin |
| Diterbitkan oleh | Gramedia Pustaka Utama |
| Terbit pada | Juli 2013 |
| Genre | fiksi, absurd, adult |
| Jumlah halaman | 241 |
| Nomor ISBN | 9789792296167 |
| Harga | IDR55.000,00 |
| Rating | 4/5 |
Mendapatkan kumpulan cerpen karya Maggie Tiojakin memiliki dua arti bagi saya:
- Sebagai sebuah keajaiban, karena begitu Tiojakin mengumumkan tentang terbitnya kumpulan cerpennya reaksi spontan saya saat itu adalah "Kali ini saya harus mendapatkannya!".
- Hal ini kemudian berhubungan dengan arti kedua: sebagai balas dendam.
Sekitar tahun 2010 (kalau saya tidak salah) Tiojakin juga menerbitkan kumpulan cerpen, yang belum saya miliki.
Thus, sewaktu Tiojakin mengabarkan bahwa ia memiliki dua eksemplar kumpulan cerpen Selama Kita Tersesat di Luar Angkasa (SKLTA) dan hendak memberikan salah satu pada saya, rasanya benar-benar seperti jawaban dari langit bagi saya :D
Nah, mari berhenti berbasa-basi dan mulai membahas tentang kumpulan cerpen ini.
Ada sekitar 19 cerpen di dalam Selama Kita Tersesat di Luar Angkasa (SKTLA), plus cerita tambahan dalam bahasa Inggris dan minus bagian ekstra. Dan dari seluruh cerpen bernapaskan absurditas saya nyaris menyukai semuanya. Tapi tiga cerpen favorit saya adalah: "Tak Ada Badai di Taman Eden", "Kota Abu-Abu", dan (tentu saja) cerpen yang menjadi judul buku: "Selama Kita Tersesat di Luar Angkasa". Namun, dalam artikel ini saya hanya akan menggunakan dua cerpen sebagai cerminan dan untuk "membaca" kumpulan cerpen dari penulis kelahiran Jakarta ini.
Baca juga: The Giving Tree: Cinta Adalah Bahasa Universal
Sekilas Cerpen dalam Selama Kita Tersesat di Luar Angkasa
SKTLA adalah pengalaman kedua saya berkenalan dengan gaya Tiojakin, yang kuat dalam mengeksplorasi karakter serta emosi tokoh. Misalnya saja pada cerpen “Tak Ada Badai di Taman Eden” (TABTE). Cerpen yang berada di halaman awal SKTLA ini berkisah tentang terlemparnya pasangan suami-istri, Barney dan Anouk, ke keterasingan. Inilah yang saya tangkap ketika membaca TABTE; keterasingan dan jarak yang muncul lewat interaksi dan kebersamaan pasangan ini:
Barney meletakkan tas kerjanya di atas konter dan menghampiri Anouk yang berdiri memunggunginya. Ia mengecup pipi wanita itu, lalu mengambil selembar serbet bersih untuk mengelap wajahnya yang basah oleh hujan.
“Kau sedang apa?”
“Menatap badai,” kata Anouk. “Aku lihat langit pecah siang tadi.”
Dari interaksi mereka terlihat bahwa, meski tinggal dalam satu atap dan berada dalam satu ruangan, namun baik Barney maupun Anouk hidup dalam dunia masing-masing. Anouk tak mengacuhkan Barney yang baru saja pulang kerja. Dia tidak menyiapkan makanan untuk suaminya, pun tidak menyambut lelaki itu ketika dia mencium pipinya. Anouk terus berdiri dengan posisi yang sama, menatap keluar, memandang badai yang terjadi di luar sana. Dan mungkin di dalam dirinya. Dalam diri mereka.
 Diambil dari etsy.com
Diambil dari etsy.com
Tidak jelas, bagaimana dan apa yang menyebabkan jarak tersebut. Hanya ada sekelumit cerita masa lalu keduanya, yang kemudian menyebabkan mereka berada pada keadaan yang sekarang: Anouk memandang badai, seolah dia menunggunya datang. Seperti dia menunggu badai menghampiri kehidupan rumah tangganya, yang hari itu ditandai dengan pecahnya ‘langit’.
Bukankah langit warnanya didapat dari pantulan laut? Dan bukankah laut adalah gambaran dari kehidupan rumah tangga, yang mesti diarungi bersama dengan bahtera?
Tentu kita setidaknya pernah sekali mendengar istilah “selamat menempuh bahtera baru”. Nampaknya, bahtera yang digunakan Anouk dan Barney untuk mengarungi samudera kehidupan mulai bocor.
Yang saya sukai dari cerpen ini adalah nuansa yang tercipta dari diksi serta interaksi karakter. Meski menceritakan perpisahan, tidak ada sedu sedan dan pertumpahan emosi berlebih, yang mengingatkan saya pada salah satu cerpen John Steinbeck dengan tema yang sama. "The Chrysanthemum". Bedanya, bila pasangan di cerpen Steinbeck, khususnya si suami, terkesan tak acuh – pasangan Barney-Anouk masih menunjukkan keinginan mereka untuk bersama.
Berikut adalah kutipan yang menunjukkan upaya Barney untuk mengulurkan tangan dan meniadakan jarak antara dirinya dan istrinya:
Tepat pukul sepuluh malam, gemuruh langit dan desauan angin kencang mengakibatkan seluruh aliran listrik dalam kota mati total. Anouk berlari masuk ke dapur, di mana Barney tengah menyalakan tiga batang lilin di ata cadelabra. Melihat wajah Anouk yang pucat, Barney tersenyum tulus.
“Tidak apa-apa,” kata Barney. “Cuma badai biasa.”
Terkadang dibutuhkan goncangan, badai dahsyat, atau lubang di bahtera, untuk menyadarkan seseorang apa yang sedang terjadi. Memberi petunjuk apa yang terpenting dalam hidup ini dan mulai menghargainya, agar tidak menghilang dari kehidupan orang tersebut. Seperti yang dilakukan Barney agar Anouk tidak menghilang dari kehidupannya. Terempas bersama badai.
Dan terkadang, seseorang harus menganggap kecil sebuah masalah dan mulai memikirkan bagaimana mengatasinya, ketimbang menganggapnya terlalu besar untuk diselesaikan. Sehingga mendorong seseorang untuk bersembunyi, tak mengacuhkannya, atau bahkan lari.
Baca juga: Intertwine - Takdir yang Berjalin
Keajaiban Tulisan Tiojakin dalam Selama Kita Tersesat di Luar Angkasa
Sejauh ini saya sudah memiliki tiga buku dari karya Tiojakin. Dua kumpulan cerpen yang diterjemahkan serta satu novel, Semenjak membaca Winter Dreams, saya segera dibuat jatuh cinta pada kepenulisan Tiojakin dan penasaran, seperti apa tulisan lain yang dihasilkannya.
Salah satu hal yang membuat saya jatuh cinta pada sebuah karya adalah diksi, konsistensi karakter, serta nuance yang tercipta. Dan ketiganya saya temukan pada tulisan Tiojakin, dengan bonus absurditas yang terselip di dalamnya. Misalnya pada cerpen berjudul “Selama Kita Tersesat di Luar Angkasa”. Cerpen ini menggambarkan kehidupan kru pesawat ulang-alik Rusia setelah mereka terdampar di sebuah planet yang sedang menyusut.
 Diambil dari menapak-cakrawala.blopspot.com
Diambil dari menapak-cakrawala.blopspot.com
Seperti layaknya kebanyakan cerpen, bahasa dan cerita yang ditampilkan oleh Tiojakin singkat dan cukup padat. Namun yang membedakan adalah bagaimana ia menghadirkan kehidupan, diikuti dengan karakter yang terasa hidup, bukan sekadar cerita buatan dengan karakter karangan. Simak saja potongan pembicaraan antara Sang Kapten dengan salah seorang awak pesawat ulang-alik:
“Aku belum siap mati,” kata Koveer.
“Hmm.”
“Menurutmu kita bisa selamat dari sini?”
Sang Kapten tidak langsung menjawab, membiarkan jeda itu tumbuh sesaat.
“Entahlah,” jawabnya kemudian.
“Aku belum siap mati,” kata Koveer.
“Berapa usiamu, Koveer?”
“Dua puluh tiga.”
“Punya pacar?”
“Belum, Kapten.”
“Apa saja yang kau lakukan selama ini?”
“Belajar untuk jadi prajurit-astronot.”
“Lihat hasil pelajaran sekarang,” kata Sang Kapten.
Koveer merasakan mulutnya kering. “Oh, sial.”
“Kenapa?” tanya Sang Kapten.
“Aku harus buang air kecil.”
Oke, memang Tiojakin mengatakan bahwa semua cerita yang diusungnya ke dalam SKTLA adalah cerita bergenre absurd – yang percaya bahwa setiap kehidupan ini adalah kesia-siaan. Kita bangun pagi, bekerja, mengisi perut – berusaha hidup setiap hari – tidak lebih dari sekadar kesia-siaan belaka. Sebab, toh, kita pada akhirnya akan mati. Tema inilah yang terasa benar dalam kisah kapten dan para awak pesawat ulang-alik tersebut. Lihat saja sikap Sang Kapten saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan Koveer.
Dalam imajinasi saya Kapten tampak acuh tak acuh terhadap awaknya, sebab dari tiap kalimat yang diucapkannya tak sedikit pun ia terdengar bersimpati pada awaknya yang sedang gundah. Hal ini bisa jadi diakibatkan pada saat itu Sang Kapten sendiri sedang galau, menyadari kemungkinan 0% ia bisa kembali ke bumi. Sehingga ia tak terlalu banyak memikirkan tentang rasa dan perasaan pada dirinya dan terhadap orang lain.
Namun di sisi lain absurditas percakapan yang dimulai oleh komentar Sang Kapten bisa dikatakan mengajari anak buahnya untuk lebih tegas dan memandang fakta di depan matanya, ketimbang membayangkan yang belum terjadi serta memandang yang telah lewat.
Baca juga: Just So Stories Sekadar Cerita
Akhir Kata dari Keabsurdan Selama Kita Tersesat di Luar Angkasa
Terlepas dari fakta bahwa absurditas membawahi gagasan mengenai kesia-siaan – percayalah, meski beberapa kali saya menemukan hal ini dalam cerpen-cerpen penulis luar negeri (Camus dan Kafka), hingga saat saya menuliskan review ini, dalam diri saya terjadi konflik. Benarkah semua yang saya lakukan adalah kesia-siaan belaka? Benarkah keterlanjuran saya hidup tidak memiliki makna?
Bila dilanjutkan tidak akan ada jalan keluar dan ujung dari semua pembicaraan. Seperti dua ular yang saling menggigit ekor (saya lupa apa istilahnya). Daripada memfokuskan diri mana yang salah dan mana yang benar, lebih baik kita memperhatikan bagaimana absurditas dan filosofi-filosofi lainnya yang saling melengkapi.
Setiap orang tentu memiliki kehidupan dan tujuan masing-masing. Beberapa ingin fokus pada apa yang terjadi saat ini – pada detik ini. Sementara yang lain ingin mencari apa dan siapa diri mereka pada di masa ini dan masa depan, serta di mana mereka akan berada nantinya. Menurut saya pribadi, tidak ada hal yang sia-sia dalam hidup ini. Sekecil apa pun peran suatu hal dan keberadaan suatu hal, ia pasti memiliki peran yang signifikan.
Your book curator,
N
Niratisaya a.k.a Kuntari P. Januwarsi (KP Januwarsi) adalah Co-Founder Artebia yang juga seorang penulis, editor, dan penerjemah.
Profil Selengkapnya >>