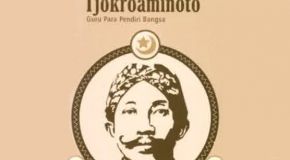Stigma dan Tradisi: Menikah - Antara Tuntunan Agama dan Tuntutan Masyarakat
23 Nov 2014 View : 5179 By : Niratisaya
“Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya yang ada di dunia ini berpasang-pasangan”
Saya lahir dan besar di dalam lingkungan keluarga besar dengan tradisi Jawa yang cukup kental. Meski saya tumbuh sebagai anak semata wayang, tetapi berkat keluarga besar saya, saya mendapatkan pengalaman lebih mengenai upacara pernikahan yang terasa begitu istimewa dan sakral.
Dulu.
Seiring perkembangan pemahaman saya terhadap sekitar, pengalaman saya mengenai upacara pernikahan menjadi berbeda 180 derajat. Wangi-wangi bunga melati, yang dijalin sedemikian rupa dengan benang hingga menjadi ronce, hiasan kepala pengantin perempuan dan penghias keris lenyap, terganti oleh bunga-bunga plastik. Meja-meja dan kursi-kursi tempat tamu undangan dan pemilik hajat biasa duduk serta berbincang hilang.
Berganti meja-meja dengan hidangan ala buffet. Sebuah pesta yang menjadi ajang menghaturkan rasa syukur berubah menjadi sekadar ajang temu muka. Amplop-amplop berisi restu kini berubah menjadi alat-alat hitung dan ukur. Setelah para tamu dan pemilik hajat bertemu, bercakap-cakap beberapa menit, dan berfoto, tuntaslah acara itu.
Apakah sih, sebenarnya pengertian pernikahan?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan adalah sebuah upacara ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama. Akan tetapi berbicara mengenai agama, tidak akan pernah lepas dari peran para penganut dan pengamalnya, manusia serta segala interpretasinya mengenai kehidupan. Yang kemudian mengaitkannya dengan kebudayaan dan kehidupan sosial.
Tapi jujur, Artebianz, apa sebenarnya upacara pernikahan—apa sebenarnya makna pernikahan?
Sebuah lembaga yang meresmikan kopulasi antara dua manusia berbeda jenis?
Sebuah media legal untuk meneruskan keturunan?
Sebuah tuntunan syariat atau sekadar tuntutan masyarakat?
Inilah topik yang ingin saya angkat di artikel meragajiwa kali ini, Artebianz. Berdasarkan kontemplasi atas percakapan saat bertemu dengan teman-teman dan pengamatan saya.
Baca juga: Ada Kemauan Ada Jalan: Sebuah Energi Kehidupan
Menikah: Stigma, Deadline, dan Tuntutan Masyarakat
“Kapan nih, mau nikah?”
“Nunggu apa lagi? Ayo, cepetan nikah.”
Sapaan-sapaan semacam itu pasti pernah Artebianz dengar dan tidak akan berhenti sampai Artebianz akhirnya menikah. Hal ini sempat saya alami sendiri, bukan sekadar disapa dengan ramah dan manis, tetapi saya langsung ditodong.
Semuanya bermula pada satu kunjungan di rumah pasangan yang bisa dibilang sebagai sosok terkemuka di desa tempat nenek saya tinggal. Sementara ayah saya berbincang dengan sosok lelaki berkulit kuning bersih yang biasa kami panggil dengan "Abah", ibu saya dan saya sendiri ngobrol dengan si istri yang kami panggil dengan "Ummi’".
Percakapan yang mulanya berputar antara kehidupan secara umum dan keadaan neneknya, entah bagaimana berubah haluan dan memasukkan saya—serta status saya sebagai salah satu jomlo—begitu Ummi’ menanyakan hal-hal pribadi. Mulai dari pekerjaan, pendidikan, dan usia. Ummi’ mengira status tersebut menempel pada saya karena betapa protektif serta konservatif ayah saya, yang bahkan tak merelakan anaknya ke luar negeri demi kuliah. Sikap protektif ayah saya tersebut membuat beliau berpikir ayah saya tidak akan mudah melepaskan putrinya untuk menikah. Mungkin anggapan beliau ada benarnya, mengingat saya adalah anak semata wayang.
“Saya yakin, Mbak akan mendapatkan jodoh yang baik. Karena Tuhan menjodohkan orang baik dengan orang baik.” Ummi’ berkata, yang segera saya aminkan. Namun kalimat berikutnya yang wanita tersebut lontarkan membuat saya termangu.
“Menikah itu sunnah Nabi, Mbak,” ujar Ummi’. “Sebagai umat Nabi Muhammad, sudah kewajiban kita untuk berkembang biak.”
Tidak sekali ini saya mendengar tentang pernikahan dan sikap memenuhi sunah nabi. Semenjak kecil, serta sejak saya membantu seorang tante saya merangkai bunga untuk pernikahan, saya paham; pernikahan adalah satu fase dalam kehidupan yang harus dijalani seseorang. Akan tetapi kata-kata “sudah kewajiban kita untuk berkembang biak” membuat saya berpikir, apakah benar pernikahan yang disunahkan Nabi Muhammad hanya berkisar pada kewajiban berkembang biak?
Amboi, Artebianz!
Betapa kata-kata itu menohok saya dan mengingatkan saya pada ayam-ayam yang dipelihara oleh adik ibu saya di belakang rumahnya. Setelah melanjutkan obrolan, yang lebih banyak saya isi dengan mendengar baik-baik dan tersenyum serta terkadang mengangguk, kami—saya dan orangtua saya—akhirnya pulang ke rumah nenek saya.
Saya sama sekali tidak bermaksud merendahkan Ummi’ dan anggapannya tentang pernikahan. Namun, saya juga tidak ingin jatuh dalam kalimat pendek menyesatkan, yang mengatakan bahwa kewajiban manusia adalah berkembang biak, untuk kemudian lari terbirit-birit dan meraih siapa pun yang saya temui—kemudian menyeretnya ke penghulu. Meski secara biologis pendapat wanita tersebut bisa dibenarkan, tetapi secara psikologis hal tersebut bisa menjadi beban.
Berkembang biak dan memiliki keturunan bukanlah akhir dari fase kehidupan sepasang manusia sebagai orangtua. Masih ada kewajiban dan tanggungan lain yang harus dijawab setelah seseorang berkembang biak. Sebab, bukankah seseorang akan menambah dosanya, bila ia tak mampu mendidik keturunannya agar bisa menjadi manusia yang mewakili keberadaan agama di dunia ini secara umum, dan Islam sendiri secara khusus; sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Selain itu, harus ada garis pembeda yang jelas antara manusia dengan hewan-hewan yang mereka pelihara. Pun, saya merasa sedikit menyayangkan—mengapa pandangan itu disampaikan seorang wanita kepada sesamanya dengan setengah-setengah? Mengapa Ummi’ menghentikan topik mengenai pernikahan di bagian “berkembang biak”?
Alih-alih pendapat dari syariat beragama, saya merasa “kewajiban menikah agar berkembang biak” adalah sekadar paham dari masyarakat umum dari nukilan dari sunah Nabi yang secara arbitrer diambil oleh masyarakat dan dijadikan kepercayaannya. Untuk kemudian menjadi sebuah “senjata” demi menodong para muda yang terlalu asyik masyuk dengan impian dan angannya.
Baca juga: Cinderella dan Wanita Masa Kini: Sebuah Dekonstruksi Dongeng
Menikah, Sunnah Nabi dan Tuntunan Syariat
Sebuah percakapan dengan wanita terpandang di desa saya tersebut, menyulut rasa ingin tahu saya, Artebianz.
Bagaimana sih, sebenarnya pernikahan menurut sunah Nabi dan tuntunan syariat?
Sebagai umat beragama, khususnya Islam, kita tentu sempat mendengar mengenai tuntunan agama mengenai pernikahan dan kisah-kisah yang berkaitan dengan hadis, yang berkaitan dengan hukum syariat yang satu itu. Sebagai salah satu umat beragama yang tinggal berdekatan dengan tempat ibadah, saya akrab dengan dua kisah pada zaman nabi menyangkut topik pernikahan.
Kisah yang pertama adalah mengenai seorang lelaki yang berkecukupan secara materi dan telah mencapai usia matang, tetapi menolak menikah. Konon, ia melakukan ini agar ia bisa berkonsentrasi dalam beribadah sehingga mampu menyamakan ibadahnya dengan tingkat ibadah Nabi Muhammad. Lelaki tersebut segera mendapat teguran dari Nabi Muhammad yang mengatakan meski beliau utusan Tuhan, beliau tetap menikah. Lebih lanjut, Nabi Muhammad menambahkan, “Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnah-ku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku.”
Dari kisah tersebut, terlihat bahwa Nabi Muhammad menganjurkan dengan sangat pada umatnya agar tidak melajang seumur hidup. Begitu kerasnya anjuran Sang Nabi, sampai-sampai beliau bahkan tega mencoret seseorang dari daftar umatnya, jika ia menolak menikah.

Keistimewaan pernikahan, menurut Nabi Muhammad, adalah ia mampu menjaga diri seseorang dari dosa. Sebab pernikahan sanggup menjaga pandangan seseorang, baik dari gunjing-menggunjing maupun dari perbuatan zina. Menurut pendapat saya, bila seseorang menikah, ia diharapkan menyadari bahwa ia tidak hanya membawa seseorang ke dalam kehidupannya, tetapi juga sebuah tanggung jawab dan tempat berbagi. Sehingga lisan dan kemaluannya tidak akan membahas dan mencampuri hal-hal di luar lingkup kehidupannya.
Selain itu, dengan menikah seseorang telah menyempurnakan separuh agamanya. Mengapa demikian? Seperti agama-agama lainnya, Islam percaya bahwa kehidupan dan tingkah polah manusia dipengaruhi oleh segala piranti yang ada dalam dirinya, terutama perut dan kemaluan. Kedua piranti dalam diri manusia tersebut mewakili nafsu-nafsu dalam diri manusia, sedangkan dari kacamata psikologi, keduanya mewakili kebutuhan dasar manusia.
Dengan melangsungkan pernikahan, seseorang diharapkan membentengi diri dari dosa berzina karena tuntutan kebutuhan dasar fisiologisnya (bernapas, makanan, air, seks, tidur, homeostatis—keseimbangan dinamis pada mekanisme pengaturan sistem kerja dalam diri secara konstan—dan ekskresi) [1].
Di lain pihak, dengan menikah, seseorang diharapkan mau dan sanggup menggiatkan diri agar tidak bermalas-malasan demi mengisi perutnya. Hal ini mengingatkan saya pada kisah lain pada zaman nabi, yang masih berkaitan dengan tema menikah.
Kisah kedua: alkisah, hiduplah seorang pemuda dari kalangan ekonomi menengah ke bawah—saya tidak terlalu ingat namanya dan mungkin juga guru agama saya tidak menyebutkan namanya, jadi mari kita namai dia Amir—yang baru saja menikah dengan kekasihnya, Amirah.
Nahas bagi Amir, hari baik pernikahannya berlangsung beberapa hari sebelum Ramadan. Sebagai pengantin baru, Amir tidak bisa menjauhkan dan menjaga dirinya dari Amirah. Walhasil, Amir beberapa kali membatalkan puasanya.
Kabar mengenai Amir yang beberapa kali membatalkan puasanya ini akhirnya sampai di telinga Nabi Muhammad. Sebagai seorang penguasa sekaligus pemuka agama pada zamannya, Nabi pun mendatangi Amir dan bertanya mengapa ia tidak mengikuti kewajiban berpuasa seperti yang lain.
Amir pun menjawab dengan jujur bahwa ia baru saja menikah dan tak mampu menahan diri dari menggauli Amirah, si istri. Nabi pun mewajibkan Amir untuk bersedekah, memberi makan penduduk termiskin.
Amir menolak, “Bagaimana mungkin Nabi. Di antara penduduk kota ini, sayalah penduduk termiskin.”
Nabi Muhammad kemudian memberi Amir kurma dan memerintahkan pemuda itu untuk “bersedekah” pada keluarganya sendiri, agar ia bertanggung jawab pada istri dan keturunannya kelak.
Dari kisah kedua tersebut, tampak jelas bahwa hakikat pernikahan menurut sunnah Nabi adalah menjaga diri dari nafsu-nafsu dan mengajari seseorang agar mampu berdisiplin diri serta bertanggung jawab. Bukan sekadar menunaikan kewajiban berkembang biak.
Baca juga: Dimas-Lissa: Pudarkan Kapitalisasi Pendidikan Lewat Sekolah Gratis Ngelmu Pring
Kapan dan Mengapa Kita Harus (Tidak) Menikah
Syarat wajib untuk menikah
Dari kisah kedua pada bagian sebelumnya, terlihat jelas bahwa sebuah pernikahan dapat menjadi perkara yang mudah sekaligus sulit dalam kehidupan kita, Artebianz. Mudah, karena kita bisa melakukannya kapan pun kita inginkan. Sulit, karena setelah menikah terlihat jelas bahwa ada syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh seseorang sebelum ia membentuk keluarga bersama orang yang dikasihinya.
Dalam kisah mengenai Amir tersirat bahwa syarat mendasar bagi orang yang menikah adalah memiliki kemampuan memimpin.
Mari ambil contoh hukuman yang diberikan Nabi Muhammad kepada Amir. Alih-alih memaksa Amir untuk membayar puasanya atau bekerja dan menafkahi fakir miskin lainnya, Nabi Muhammad meminta Sebagai seorang suami, Amir diharapkan mampu menjadi sosok pengayom dan memberi kesan bahwa ia seorang pemimpin yang bertanggung Amirah, istrinya.
Namun, apakah cukup sosok laki-laki yang menjadi pemimpin? Sementara sebuah rumah tangga tidak jauh berbeda dengan sebuah negara yang membutuhkan seorang presiden dan wakilnya.
Dalam ajaran Islam ada sebuah hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan. Hadis tersebut menyebutkan bahwa:
“Tiap seorang daripada kamu adalah penjaga (pemimpin) dan kamu bertanggungjawab terhadap penjagaan kamu (orang yang dipimpin). Imam adalah penjaga (pemimpin) dan bertanggungjawab kepada pimpinannya, lelaki itu penjaga (pemimpin) dan bertanggungjawab kepada pimpinannya, orang perempuan adalah penjaga (pemimpin) dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab kepada pimpinannya, hamba adalah penjaga harta tuannya dan bertanggung jawab kepada pimpinannya, dan setiap kamu adalah penjaga (pemimpin) dan bertanggungjawab kepada pimpinan kamu." (Riwayat Muslim).
Secara eksplisit hadis riwayat Muslim tersebut menyebutkan bahwa bukan hanya laki-laki saja yang memiliki kewajiban menjadi pemimpin, tetapi juga seorang wanita. Tanpa memedulikan status atau jenis kelamin, setiap dari kita adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab pada pimpinan kita (Tuhan). Dengan keyakinan demikian, rasanya seseorang tidak akan dengan mudah mengambil keputusan menikah kemudian bercerai, seperti yang marak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Atau menikah beberapa kali.
Baca juga: Takdir dan Pertanda-Pertanda
Menikah ternyata haram kalau….
Yes, Artebianz, ternyata di antara sunnah yang menyarankan dan mewajibkan pernikahan, ada pula yang mengharamkan terciptanya lembaga ini antara seorang laki-laki dan wanita. Namun, sebelum kita membahas mengenai haramnya menikah, mari kita bahas hukum-hukum menikah lainnya terlebih dulu.
Jika dilihat dari kondisi mereka yang akan melaksanakannya, hukum menikah dibagi menjadi lima:
1. Menikah hukumnya wajib ketika seseorang memiliki hasrat yang tinggi karena tak mampu mengendalikan nafsu syahwatnya, sementara di sisi lain, orang tersebut mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Oleh sebab itu, agar terjerumus dalam gelimang dosa karena perzinaan, mereka yang berada dalam kondisi ini diwajibkan untuk menikah.
Atau… bagi seorang pelajar (catat ya, Artebianz, pelajar yang berusia di atas tujuh belas tahun), yang tak mampu berkonsentrasi dalam belajar karena selalu memikirkan pernikahan—apabila si pelajar ini berpura-pura konsentrasi belajar atau membaca buku, tapi ternyata hanya berpura-pura—maka si pelajar ini wajib untuk menikah.
Tentu saja, syarat kemampuan materi dan fisik, serta kesanggupan untuk bertanggung jawab atas masa depan si pelajar itu sendiri dan pasangannya, perlu diperhatikan. Selain itu, pertimbangan bahwa dengan menikah semangat si pelajar untuk menyelesaikan studinya juga perlu diperhatikan.
2. Menikah hukumnya sunnah ketika seseorang memiliki nafsu syahwat dan kemampuan ekonomi, tapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinaan. Mengenai kesunahan hukum menikah Imam Nawawi dalam Syareh Shahih Muslim membahas hal ini pada Kitab Nikah dengan judul “Bab Dianjurkannya Menikah Bagi Orang Yang Kepingin Sedangkan Dia Mempunyai Harta” (An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, juz: 9, halaman: 172).
3. Menikah hukumnya mubah (tidak berdosa dan tidak berpahala bila dilakukan) ketika seseorang didesak oleh syahwatnya, tapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan. Atau bagi mereka yang berkecukupan secara ekonomi, tapi tidak mempunyai nafsu syahwat yang mendesaknya untuk menikah. Dari referensi yang saya temukan mengenai hukum menikah, contoh ini disebutkah oleh Syekh al-Utsaimin di dalam Syarh Bulughul Maram (juz: 4, halaman: 180).
4. Menikah hukumnya makruh bagi mereka yang tidak memiliki harta dan keinginan menikah (lemah syahwat). Kemakruhan hukum menikah bagi mereka dengan kondisi demikian adalah karena sebenarnya ia belum membutuhkan pasangan untuk dinikahi, serta sedang berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu.
Bila mereka dalam kondisi ini dipaksakan untuk menikah, dikhawatirkan pasangannya tidak akan terurus dan masing-masing akan berkutat dengan kesibukan masing-masing, sehingga pernikahan sama sekali tidak memiliki makna di antara keduanya.
5. Menikah hukumnya haram bagi mereka yang merasa dirinya tidak mampu bertanggung jawab dan akan menelantarkan istri dan anak. Atau jika dari sudut pandang seorang wanita, menurut hadis riwayat Muslim, bila si wanita tidak mampu bertanggung jawab, dalam hal ini memimpin diri sendiri dan rumah tangganya.
Baca juga: Indah Kurnia, Memimpin Tanpa Kehilangan Identitas Sebagai Wanita
Kesimpulan: Menikah, Pada Akhirnya….
Tentu saja, siap atau tidak siap, pernikahan tidak terelakkan dari fase kehidupan seorang manusia. Dan semuanya kembali lagi pada pribadi kita masing-masing, Artebianz, apakah kita akan menikah dan menutup mata terhadap segala kemungkinan yang terjadi di masa depan.
 Diambil dari ahmadgaus.com
Diambil dari ahmadgaus.com
Atau kita bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang, dengan menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita terlebih dulu. Agar ketika menikah, kita tidak akan berputar-putar pada hal yang justru akan menyebabkan bahtera yang kita arungi bersama pasangan kelak berputar-putar mengikuti arus kehidupan tanpa memiliki kendali pada kemudi.
Semoga kita semua bisa menempuh bahtera kehidupan dengan baik, Artebianz 
Baca juga: Mengasah Rasa Lewat Kehidupan dan Gelombang Ujian
Catatan kaki:
[1]
Hirarki kebutuhan dasar menurut teori Abraham Maslow.
Referensi:
- http://almanhaj.or.id/content/3565/slash/0/anjuran-untuk-menikah/
- http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/271/pengertian-menikah-dan-hukumnya/#_ftnref25
Niratisaya a.k.a Kuntari P. Januwarsi (KP Januwarsi) adalah Co-Founder Artebia yang juga seorang penulis, editor, dan penerjemah.
Profil Selengkapnya >>